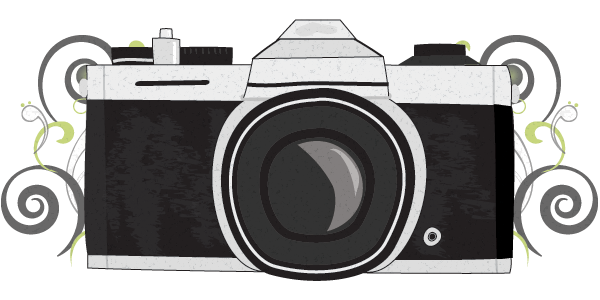Disclaimer: Sebenernya isinya tentang caraku coping stress bukan cuma self-talk, tok. Judulnya biar catchy doang sih, biasa, jiwa-jiwa clickbait 🙂
Disclaimer: Sebenernya isinya tentang caraku coping stress bukan cuma self-talk, tok. Judulnya biar catchy doang sih, biasa, jiwa-jiwa clickbait 🙂
Fotonya ngambil dari Twitter lupa sumbernya. Kalau anda yang punya bilang aja nanti saya tulis sumbernya di sini hehe. Maaf ya nggak bilang dulu.
“Kamu kalau lagi stres biasanya ngapain?”
Pernah suatu hari seorang teman nanya gini. Tadinya mau aku jawab pake bercandaan, tetapi rupa-rupanya beliau justru lagi butuh saran. Kebetulan beliau sedang cukup didera berbagai macam hal saat itu. Jadi, aku jawab dengan serius.
“Kalau aku sih biasanya karaoke,” Kenapa karaoke? Karena buat aku yang cenderung menyimpan semuanya sendiri ini bisa jadi media ngeluarin emosi-emosi negatif yang belum bisa aku izinkan buat keluar. Kalau lagi sedih bisa nyanyi lagu sedih, lagi marah bisa teriak-teriak di lagu apapun, lagi capek bisa nyanyi lagu-lagu comfort punya hyung dan noona dari Korea sana. Seenggaknya bisa sedikit meringankan emosi yang numpuk, kebendung, dan belum sempat dilampiaskan.
“Selain itu, aku sering banget nulis sih,” Klise banget yang ini mah haha. Dari SMA aku udah mulai aktif nulis sebenernya, cuma yang beneran nulis buat relieving stress tuh baru sering pas udah kuliah. Medianya banyak. Kalau yang private dan agak triggering biasanya aku tulis di buku khusus atau di akun medsos alter. Kenapa? Karena meskipun aku butuh suatu tempat buat buang stres, ya jangan numpahin stresnya ke orang lain juga hehe. Kalau yang aku rasain cukup ‘lulus sensor’ biasanya aku tulis di sini, di twitter, atau di medsos lain.
Makanya mohon maaf ya kalau kadang apa yang aku tulis di medsos vibe-nya cukup depresif dan dark. Itu udah lulus sensor pribadi kok wkwk. Tulisan-tulisan depresif yang utamanya banyak dijumpai di twitter aku itu juga ada maksudnya kok selain buat ‘caper’. Itu bentuk kejujuran aku buat diri aku sendiri, I allow myself to feel some certain feelings and let them go, salah satunya lewat tulisan itu. Aku jujur ke diri aku bahwa, ya aku sedang sedih, kecewa, marah, dll dan itu wajar, I am a human afterall. Dan semua manusia wajar buat ngerasa buruk di beberapa waktu. Life is not all about sunny days and rainbows. Kadang gerimis, kadang badai. Dan aku mengizinkan itu semua datang dan aku mengizinkan semua itu pergi.
Kedua, tulisan-tulisan itu aku maksudkan buat jadi media kejujuranku buat orang lain. Sedikit cerita, setahun lalu aku menyadari ternyata aku punya tendensi untuk bikin orang lain seneng dengan kehadiranku. Bahasa kerennya aku itu people-pleaser. Lebih dalam lagi, aku ngerasa bertanggungjawab atas apa yang orang lain rasakan ketika ada aku di ruangan yang sama. Dan itu nggak sehat. Sangat nggak sehat. Lambat laun, mulai tertanam mindset “aku nggak boleh sedih di depan orang.” Padahal sedih itu manusiawi, iya kan? Balik lagi ke paragraf atas, itu artinya aku nggak ngizinin rasa sedih itu datang dan akhirnya nggak bisa ngizinin dia buat pergi. Suatu hari, aku disadarkan bahwa perasaan orang lain itu bukan urusan kita. Kita boleh kok sedih, kecewa, terpukul, dan lain-lain. Tapi karena mindset tadi udah cukup mendarah daging, susah buat diilangin jadinya. Satu-satunya cara buat jujur ke orang lain ya jadinya aku tumpahkan di medsos. Maksud aku nulis di sana sebenernya supaya orang-orang tahu kalau mungkin ada masanya aku butuh bantuan. Kalau mereka bisa bantu, ya alhamdulillah. Seenggaknya mereka tahu kalau orang kayak aku juga ada masa down-nya. Jadi cuitan cuitan itu bukan cuma buat caper ya kawan kawan yg budiman.
Satu yang jarang aku ceritain (atau malah nggak pernah) ke orang-orang. Aku sering banget self-talk alias ngomong sama diri sendiri. Aneh ya?
I’ve been doing that for 5 years. Awalnya dulu aku sempat ada masalah adaptasi dan cultural shock pas baru masuk kuliah dan karena nggak ada tempat buat cerita akhirnya aku ketemu psikolog di BK kampus. (note: ini juga buat encourage temen-temen kalau nggak apa-apa banget buat datang ke psikolog/psikiater ketika emang dirasa butuh. strong people face and solve their problems, right?) Long story short, aku disaranin buat coba self-talk.
“Kalau susah buat kamu cerita ke orang lain, coba cerita ke diri sendiri.”
Hah? Mohon maaf, saya nggak salah denger nih mbak? (dalam hati)
Buat aku pribadi itu terdengar sangat aneh. Ya gimana kita bisa dapet solusi dari diri kita sendiri yang lagi ngalami masalah yang kita ceritain? Aneh banget kan? Sampai akhirnya aku putusin buat coba lakuin itu. Gimana pun itu mbaknya yang ngasih saran udah kuliah psikologi ya masa ngaco wkwk
Dan berikut hal yang aku rasain setelah 5 tahun mempraktikan self-talk. Ini hanya berdasar pengalaman aja ya jadi ga ada dasar ilmiahnya hehe
Yang pertama adalah skill bahasa Inggris aku nambah. Ini sangat pribadi karena kayaknya cuma aku doang yang dapet faedah kayak gini haha Tapi ini bukan bercanda ya. Orang-orang yang pernah aku curhatin hal-hal berat pasti tahu kalau aku ngga nyaman ngomongin masalah yang lagi banget aku hadapin pakai bahasa sehari-hari, entah itu Jawa atau Indonesia. Mau nggak mau ya aku curhat pake bahasa Inggris. Sisi positifnya, stres berkurang, skill bahasa Inggris nambah.
Kedua, self-talk ngebantu aku menyortir hal yang mana aja yang patut dipikirkan. Ini sangat membantu buat ngurangin overthinking. Ketika aku cerita ke diri aku sendiri, seringkali tiba-tiba muncul pikiran “lah iya, ngapain aku mikirin ini ya?”. Pada akhirnya itu sangat ngebantu ngurangin stress.
Self-talk juga ngebantu aku menguraikan sebenernya masalahnya itu apa sih. Ibarat benang kusut, self-talk ngebantu aku ngerapihin helai demi helainya. Ketika cerita meskipun itu ke diri sendiri, kita pasti nyusun kalimat per kalimatnya supaya bisa dimengerti. Ngga jarang aku ngeralat kata-kataku meskipun itu aku ceritain ke diri sendiri yang udah pasti ngerti sama bahasannya. Dan believe it or not, seringkali jawabannya datang pas lagi cerita kayak gitu.
Ternyata dari DM temen-temen di Instagram, beberapa orang sering mengalami dilema antara nyemangatin dan ngehujat diri sendiri. Pun aku. Dan ini wajar kok ternyata. Yang paling penting adalah gimana cara ngehandle-nya. Usaha dan cara orang-orang mungkin beda. Tapi kalau aku biasanya gini. Pertama aku kasih nama bagian dari pikiran yang ngehujat itu sebagai ‘kakak jahat’, meminjam istilah the inner mean girl yang pernah aku baca di suatu tempat. Aku kasih nama dia karena meskipun itu ada dalam pikiranku, dia tetap bukan aku. Lebih tepatnya aku menolak dia sebagai bagian dari diriku. Dia orang lain yang jahat. He’s just another bad person. Apapun yang dia katakan tentang aku, seburuk-buruk apapun itu, it doesn’t define me at all. Aku nganggep dia sebagai orang luar. Di sini self-talk bekerja. Ketika dia berulah alias ngoceh, aku biarin dia ngoceh semaunya. Aku dibilang jelek, item, produk gagal, nggak berguna, investasi bodong, semua aku biarin, semua aku dengerin. Sampai semua udah aku dengerin baru deh aku jawab dengan jawaban seolah yang ngomong itu adalah orang lain. Susah sih, dan kadang kalau lagi ngga 100% it doesn’t work juga hehe but at least I’ve tried. Tapi percobaan berhasilnya juga tetep ada kok dengan metode ini. Silahkan dicoba barangkali cocok hehe
Meskipun aku rajin journalling dan sebagian besar membantu, tapi kadang aku juga butuh pernyataan verbal bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan nggak dipungkiri, kadang nggak ada orang yang bisa bilang itu ke aku. Kalau udah kayak gini, biasanya aku bakalan ngomong ke diri sendiri, “Nggak apa-apa, Do. Besok kita coba lagi.” atau “Pelan-pelan, Zein. Satu-satu. Semua bakal baik-baik aja, kok.” Poin pentingnya adalah meskipun ngomong sendiri, aku tetap pakai nama panggilan seolah-olah itu berasal dari orang lain. Kalau ini aku minjem tips buat nyemangatin diri sendiri (lupa sumbernya). Katanya menyebutkan nama pas nyemangatin diri sendiri lebih efektif dibanding bilang “Aku bisa!”. Aku nyontek cara itu dan cukup membantu. Bagian ini juga sering aku pakai buat ‘berantem’ sama si kakak jahat hehe.
Sekian. Semoga dalam masa pandemi ini kita semua sehat fisik dan mentalnya, ya. In case, kekeosan ini bikin kalian khawatir dan sebagainya, semoga apa yang aku share ini bisa ngebantu kalian coping with your stress ya meskipun ini bukan studi ilmiah dll. Maaf kalau berantakan dan nggak jelas hehe
Warm hugs.